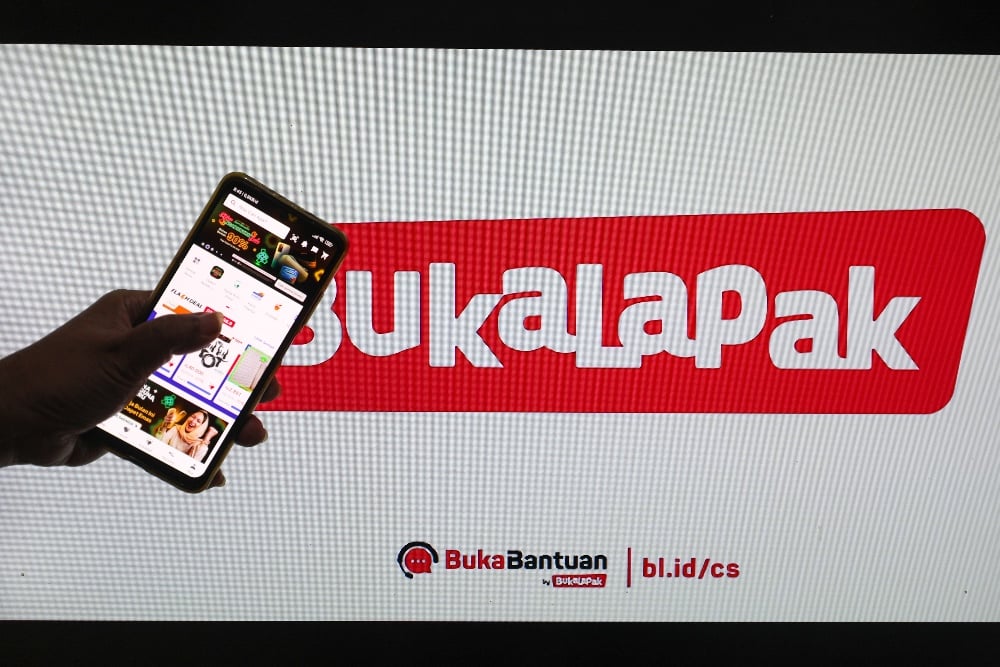Wisata Musik, Potensi yang Diabaikan
Jakarta, PaFi Indonesia — Setiap tanggal 9 Maret Indonesia merayakan Hari Musik Nasional. Tanggal tersebut diambil karena bertepatan dengan hari kelahiran Wage Rudolf Supratman, sang pencipta lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’.
Selain olahraga dan kuliner, musik juga menjadi potensi wisata yang bisa dikembangkan. Lihat saja berbagai festival musik besar yang diadakan tahunan. Jangankan hanya di Jakarta, yang diadakan di perbatasan pun minimal didatangi penduduk negara tetangga, Malaysia atau Singapura.
Konsep music tourism (wisata musik) memang baru gencar dikumandangan oleh Kementerian Pariwisata di bawah kepemimpinan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Namun jauh sebelum Java Jazz atau Djakarta Warehouse Project menjadi bagian dari promosi wisata musik di Tanah Air, negara di belahan dunia lain sudah “kenyang” melakukannya.
Contohnya Inggris, negara yang menyumbang sejarah musik dunia. Kawasan Abbey Road dan Festival musik Glastonbury bukan satu-satunya alasan para pecinta musik menyebut Britania Raya sebagai “Mekkah” industri musik.
Tahun lalu, badan yang dibentuk untuk mengurus segala hal tentang industri musik di Britania Raya, UK Music, merilis data tentang wisata musik tahun 2016.
Faktanya cukup mencengangkan.
Pada tahun itu, sektor wisata musik di Inggris meraup keuntungan sebesar £4 miliar (lebih dari Rp76 triliun), atau meningkat 11 persen dibanding tahun sebelumnya. Di tahun yang sama, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke sana sebanyak 19 juta orang. Indonesia menyumbang jumlah kedatangan sebanyak 32 ribu.
Ibiza juga demikian. Kawasan perairan yang berbatasan dengan Spanyol dan Laut Mediterania itu juga sampai sekarang masih ditasbihkan sebagai Pulau Pesta, karena setiap hari sepanjang minggu ada saja pesta musik yang digelar di sana.
Thailand dengan Full Moon Party atau Festival Bulan Purnama di Phuket ikut disebut sama. Menyusul Singapura, yang setiap tahunnya disambangi oleh konser musisi internasional.
Jika ada yang berdalih Inggris, Ibiza, Thailand, atau Singapura sudah lebih dulu memulai konsep wisata musik, maka ada baiknya melirik India. Mengutip happytrips, Festival musik elektronik Sunburn Festival yang digelar pada tahun 2015 berhasil mendatangkan lebih dari 1,5 juta pengunjung.
Wisata musik bisa marak karena atraksi wisata itu memberi pengalaman “spiritual” bagi para pengunjungnya, mulai dari merencanakan kedatangan ke suatu kawasan sampai menikmati musiknya.
Contohnya festival musik elektronik. Ada banyak kelab malam di negara asal para turis, tapi mereka lebih senang datang ke kawasan baru untuk menikmatinya, seperti di pinggir pantai atau di atas gunung. Bonus pemandangan alam jadi nilai lebih.
Berharap pada Java Jazz?
Jika ditarik ‘garis keturunannya’ musik sejatinya merupakan bagian dari wisata budaya, dan Kementerian Pariwisata telah mengakui bahwa keunggulan pariwisata Indonesia bertumpu pada potensi budaya.
“Potensi budaya mendapat porsi paling besar yaitu 60 persen, potensi alam sebesar 35 persen, dan diikuti dengan potensi buatan manusia yang mendapat porsi sebesar lima persen,” ujar Esty Reko Astuti, yang saat itu menjabat Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar pada akhir bulan Juli 2017.
Dalam katalog ‘100 Wonderful Event Indonesia 2018’ yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata, ada 10 acara nasional ditentukan oleh tim kurator sebagai acara pilihan di Indonesia.
Satu-satunya acara yang terkait musik dalam daftar tersebut adalah ‘Java Jazz Festival’, festival yang dianggap banyak netizen tak lagi “nge-jazz”.
Berdasarkan tesis karya Nuran Wibisono berjudul ‘Potensi Pariwisata Musik Sebagai Alternatif Pariwisata Baru di Indonesia (Contoh Kasus Java Jazz)’, diperkirakan sebanyak 110 ribu orang menyaksikan festival yang diselenggarakan selama tiga hari itu.
Misalkan tiap penonton menghabiskan Rp200 ribu, Nuran melanjutkan, maka jumlah pengeluaran untuk makanan dan minuman adalah Rp22 miliar.
Andai nominal itu menyetor pajak 10 persen saja, maka paling tidak Pemprov DKI mendapatkan Rp2,2 miliar hanya dari satu acara. Selain makanan dan minuman, suvenir juga menjadi pemasukan yang menguntungkan bagi penyelenggara festival.
Salah satu suvenir paling popular di sana adalah kaus. Pada 2015, penyelenggara memproduksi kaus sebanyak 6.000 helai dengan harga Rp150 ribu. Kaus yang dijual terjual habis. Ini artinya ada pemasukan Rp900 juta hanya dari penjualan kaus.
Jika berkaca pada salah satu contoh kasus seperti yang dituliskan oleh Nuran Wibisono, maka sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar dalam wisata musik. Tapi, tetap saja ada pekerjaan rumah yang tak kunjung diselesaikan.
Pulau Jawa melulu
Beberapa hari lalu, tepatnya mulai Rabu (7/3), sebagian besar pelaku di industri musik di Indonesia berkumpul di kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam rangka menghadiri Konferensi Musik Indonesia (KAMI) yang pertama.
Acara yang digagas oleh musisi asal Ambon, Glenn Fredly, itu menghadirkan banyak pembicara yang kompeten di bidangnya seperti David Tarigan (Pendiri Irama Nusantara), Indra Ameng (Manajer White Shoes & The Couples Company), hingga Triawan Munaf (Kepala Badan Ekonomi Kreatif), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan masih banyak lagi.
Selama dua hari, acara tersebut fokus membedah musik dari beragam persepektif mulai dari industri, diplomasi budaya, dan edukasi. Salah satu pembicara sekaligus penulis musik, Idhar Resmadi, berbagi cerita kepada PaFiIndonesia.com tentang acara tersebut khususnya untuk kasus wisata musik.
Idhar mengatakan kendala di Indonesia untuk mengembangkan wisata musik adalah infrastruktur penunjang.
“Contohnya Ambon, kota ini emang edan banget musiknya! Banyangin aja di setiap sudut ada panggung buat musisi. Tapi sayangnya di sini taksi gak ada, apalagi transportasi berbasis online? Sinyal aja susah,” ujar penulis biografi band indie legendaris asal Bandung, Pure Saturday.
Selama dua hari konferensi berlangsung, Idhar melihat bahwa Kementerian Pariwisata masih memfokuskan alam sebagai lokomotif pariwisata Indonesia. Andaikan ada dukungan dari Kementerian Pariwisata terkait wisata musik, itu baru sebatas promosi dan pertunjukan musik di destinasi.
Menurutnya juga pusat dari wisata musik masih sebatas kota-kota besar di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Sebatas sekaligus juga terbatas, tengok saja Bandung, kota yang berjarak dua jam perjalanan lewat tol dari Jakarta. Di sana, izin menyelenggarakan acara musik bisa dibilang lebih rumit dibandingkan izin mendirikan hotel.
“Mengembangkan wisata musik itu harus mengalahkan ego berbagai pihak dulu. Semua lembaga yang terkait harus terintegrasi, misalnya Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR, dan lainnya. Semua harus duduk bareng untuk membahas ini,” kata Idhar.
“Anak Indie” sudah duluan
Terkait musik dan pemandangan, Agus Setiawan Basuni selaku salah satu pendiri media Warta Jazz, tidak menampik bahwa acara-acara yang diselengarakan oleh pihaknya memang memadukan kedua unsur tersebut. Yang terbaru adalah Maratua Jazz & Dive Fiesta.
“Kami memang memadukan unsur musik dan panorama, karena pemandangan di Maratua sangat istimewa. Bayangkan, menantikan momen matahari tenggelam di pantai sambil dihibur pertunjukan musik jazz. Kemarin cukup banyak juga yang datang dari luar negeri,” ujar Agus saat ditemui PaFiIndonesia.com pada beberapa waktu lalu.
Belakangan ini, memang cukup banyak pihak yang memadukan musik dan panorama sebagai paket pertunjukannya, khususnya komunitas musik independen. Sebut saja Float2Nature, RRREC Fest in The Valey, dan terakhir Lazy Hiking Club.
Bahkan tak jarang mereka berkolaborasi untuk membuat sesuatu yang segar dan membawa keuntungan ekonomi bagi warga sekitar destinasi wisata.
Jadi, jika “anak indie” sudah mulai berkolaborasi mengembangkan wisata musik, kapan pejabat beserta lembaga pemerintahannya mulai menyatukan visi untuk memfokuskan wisata musik sebagai alternatif pariwisata baru di pelosok Indonesia?